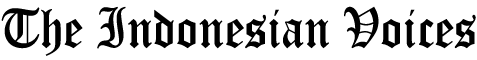Hari-hari ini, kita menyaksikan -kalau bukan ikut-ikutan- sebuah drama-tragedi yang menuntun kita pada satu simpulan: ada yang lepas dari ingatan kita sebagai sebuah bangsa. Utamanya, tentang siapa diri kita. Sehingga perlu rasanya kita merenungkan kembali sambil bertanya dalam hati: Apa yang membuat 1.340 suku dengan 1.158 bahasa daerah setempat (BPS, 2010) bisa seia sekata berpayung Indonesia?
Saya lebih suka menjawab seperti apa yang digaungkan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker: “ada perasaan senasib sepenanggungan, terikat oleh pahitnya penjajahan.” Yang menarik, kalimat itu menggema jauh sebelum hiruk pikuknya sidang-sidang di Pejambon menjelang pertengahan 1945 itu. Semacam ada usaha untuk mendefinisikan siapa kita: sebuah bangsa yang majemuk. Yang menariknya lagi, telaah itu justru dimulai dari mulut seorang Indo (sebutan untuk mereka yang bukan keturunan murni Eropa –red), dalam secarik suratnya untuk ratu Belanda pada 1913: “Tidak, Yang Mulia… negeri ini bukan negeri milik Anda. Negeri ini adalah negeri milik kami, tanah air kami…”
Kita semestinya bertanya: Apa maksud “tanah air kami” bagi seorang Indo? Bukankah nenek moyang anda telah demikian kejamnya pada kami yang Bumiputra, menjadikan kami tak lebih dari seekor budak? Lantas, dengan entengnya anda mengatakan seolah anda bagian dari kami? Saya bisa membayangkan pelbagai satire, bahkan kecurigaan yang dialamatkan pada diri Douwes Dekker. Namun, sosok yang lahir di Pasuruan, 8 Oktober 1879, berdarah jawa dari sang bunda itu tak kenal surut. Ia berpendirian keras. Baginya, Hindia atau Indonesia bukan sekadar tempat di mana ia lahir. Ada sesuatu yang mengikatnya dan merasa jadi bagian terbesar hidupnya. Sesuatu yang mesti diperjuangkan.
Karena sikapnya itu, DD, begitu ia akrab dipanggil, keluar dari Indische Bond setelah sebelumnya terus mengkritik langkah perkumpulan orang-orang Indo itu, yang baginya, lembek dan justru mengemis pada Belanda: cukup dengan hidup nyaman dan tak mengganggu kepentingan Belanda atas tanah jajahannya. Sesuatu yang tentu ditentang DD.
Risiko bagi seorang seperti DD, pasti ia jadi seorang yang terkucil di komunitasnya sendiri, yang sebelumnya, sejak awal, ia pun memang seorang asing di tengah-tengah mereka yang ia bela –yang kerap diejek oleh suku bangsanya sendiri sebagai inlander. Dari situ, pernahkah DD mengeluh dan bertanya: Sekat itu selamanya tak akan hilang, itu niscaya, tapi, bisakah puak “kami” dan puak “mereka” setidaknya berembuk, mengatas-namakan “kita” untuk mengatakan: penjajah itu harus angkat kaki dari bumi pertiwi dengan segera?

DD beruntung, ia bertemu orang-orang yang percaya akan keteguhan sikapnya itu. Salah duanya datang dari Bumiputra: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Bersama mereka, DD terus mendorong arti yang pas untuk mengisi pengertian dari sebuah bangsa baru yang mendiami negeri yang merdeka kelak. Dalam majalah Hindia Poetra tahun 1918, proposal itu kian tampil berani: “Bangsa Indonesia ialah siapa saja yang menganggap Hindia atau Indonesia tanah airnya, tak peduli apakah ia orang Indonesia totok, keturunan Tionghoa, Belanda, atau Eropa. Siapa pun warga negara Indonesia adalah orang Indonesia,” jelas Tiga Serangkai itu.
Barangkali, pada akhirnya, semangat DD itulah yang juga menginspirasi para pemuda untuk berembuk di Batavia, mereka berikrar: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Persatuan –yang belakangan kita mengenalnya sebagai Sumpah Pemuda 1928. Tentu tak habis pikir. Sebelum dimaklumkannya sumpah itu, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Bataks Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPPI, Pemoeda Kaoem Betawi, dan lain-lain, apakah pula berpikir jauh: rumusan mereka itu -seperti cita-cita DD di atas- punya konsekuensi yang tak gampang untuk dijalankan, cukupkah modal senasib sepenanggungan itu dijadikan alasan untuk sesuatu yang justru sangat rentan nantinya akan sebuah pertikaian?
Dari situ, kita semestinya selalu tertegun ketika mendefinisikan siapa kita, sebuah uji-coba yang sulit untuk mencari titik temu antar pelbagai suku bangsa –dan bersepakat. Maka harus diakui, merawat Indonesia itu susah. Dan susah itu berarti bukan tak bisa, saya rasa, yang buat Indonesia tak akan seperti misalnya Yugoslavia yang pecah (pluralnya tak kalah seperti Indonesia –red) ialah adanya sebuah kerendah-hatian untuk tak mencibir atau menghina yang-lain, yang-berbeda. Kita punya modal besar itu. Memang ada yang begitu galak mengartikan siapa kita, tapi saya kira itu hanya sebagian kecil kita. Mayoritas kita, saya yakin, justru punya kerendah-hatian + akan ditempuhnya rembukan untuk mencari titik temu bila ada masalah, sikap-sikap yang merupakan hasil tempaan sejarah dan jadi semacam tradisi. Dan toh, kita masih tetap eksis dan akan terus eksis.
Teruslah eksis untuk tak surut seperti apa yang diperjuangkan DD. Kita mesti belajar dari sosok yang satu ini, apalagi ia bukanlah seorang Bumiputra, ia seorang Indo yang justru memilih Indonesia sebagai tanah airnya, memilih bumi pertiwi sebagai tanah perjuangannya. Maka, sisihkan waktu kita sedikit untuk merenungkan gagasannya soal siapa itu bangsa Indonesia. Tentu, dengan diawali sikap optimis atas kemajemukan Indonesia, juga sikap Berani Bersatu Membela Keberagaman.
#BeraniBersatuMembelaKeberagaman